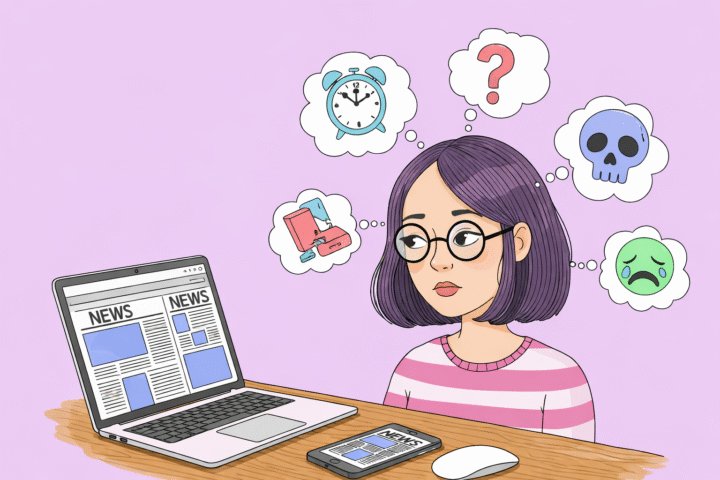TENTANGPUAN.com – Komunikasi adalah inti dari setiap relasi, entah itu dalam rumah tangga, pertemanan, atau lingkungan kerja.
Namun, dalam konteks relasi heteroseksual, sejumlah riset menunjukkan adanya pola yang berulang: laki-laki cenderung lebih ingin didengar daripada mendengar, terutama saat terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat.
Fenomena ini bukan hanya soal kebiasaan komunikasi, tetapi terkait erat dengan konstruksi sosial yang membentuk bagaimana laki-laki dan perempuan belajar mengekspresikan emosi dan menangani konflik sejak kecil.
Bukti Riset: Laki-laki Lebih Dominan dalam Konflik Verbal
Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Deborah Tannen, profesor linguistik di Georgetown University, mengungkap bahwa laki-laki cenderung menggunakan komunikasi untuk membangun status atau dominasi, sedangkan perempuan menggunakannya untuk membangun kedekatan dan koneksi emosional.
Dalam konflik, laki-laki sering merasa perlu “memimpin” arah pembicaraan, menyelesaikan persoalan secara logis, bahkan memotong pembicaraan saat merasa tidak setuju.
Studi lain oleh Journal of Social and Personal Relationships (2021) juga menunjukkan bahwa dalam konflik pasangan heteroseksual, laki-laki lebih sering melakukan interruption (menyela pembicaraan) dan kurang menunjukkan active listening dibandingkan perempuan.
Sementara itu, perempuan dalam studi yang sama menyatakan merasa “tidak didengar”, bahkan saat sedang membicarakan pengalaman emosional yang penting.
Situasi ini seringkali memperburuk konflik, karena tidak terjadi proses saling memahami, melainkan saling mendominasi.
“Aku Cuma Ingin Didengar, Bukan Diceramahi”
Bagi banyak perempuan, pertengkaran seringkali bukan soal mencari solusi cepat, tetapi tentang kebutuhan untuk divalidasi: “Aku sedih,” “Aku kecewa,” atau “Aku marah karena kamu mengabaikanku.”
Namun, respons laki-laki sering kali berupa pembelaan, logika, atau upaya mengakhiri percakapan secepat mungkin, dengan dalih “nggak usah diperpanjang.”
Kondisi ini diperparah oleh budaya yang menganggap perempuan terlalu emosional dan laki-laki sebagai pemikir rasional.
Padahal, mendengarkan bukan soal logika atau emosi, tetapi soal kemauan untuk hadir dan memahami.
Dampaknya Perempuan Terpaksa Diam atau Meledak
Saat suara perempuan terus-menerus tidak didengar dalam konflik, mereka cenderung menarik diri, menjadi pasif-agresif, atau justru meledak dalam frustrasi.
Dalam relasi yang tidak sehat, ini bisa berkembang menjadi pola relasi toksik, bahkan kekerasan emosional.
Tidak jarang, perempuan akhirnya mengalah demi “menjaga suasana”, padahal perasaan mereka tak pernah sungguh-sungguh ditanggapi.
Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi kesehatan mental, rasa percaya diri, bahkan kestabilan hubungan.
Perlu Edukasi dan Kesadaran Baru
Mengubah pola komunikasi tidak cukup hanya dengan nasihat “harus saling mendengarkan”. Perlu edukasi sejak dini tentang pentingnya empathy listening, terutama bagi anak laki-laki yang sejak kecil diajarkan untuk “kuat” dan tidak menunjukkan kelembutan dalam dialog.
Pasangan juga perlu membangun ruang komunikasi yang aman, di mana perempuan bisa berbicara tanpa takut dianggap “berlebihan”, dan laki-laki belajar bahwa menjadi pendengar yang baik tidak membuat mereka kehilangan harga diri—justru itulah bentuk kedewasaan emosional.
Mendengarkan Adalah Tindakan Revolusioner
Di dunia yang sering kali membungkam suara perempuan, kemampuan laki-laki untuk sungguh-sungguh mendengar bukan hanya bentuk cinta, tapi juga tindakan politik.
Mendengarkan berarti mengakui bahwa suara perempuan setara pentingnya, terutama dalam konflik.
Karena dalam pertengkaran, yang sering kali paling dibutuhkan bukanlah solusi—tetapi pengakuan, empati, dan ruang untuk merasa bahwa suara kita berarti.