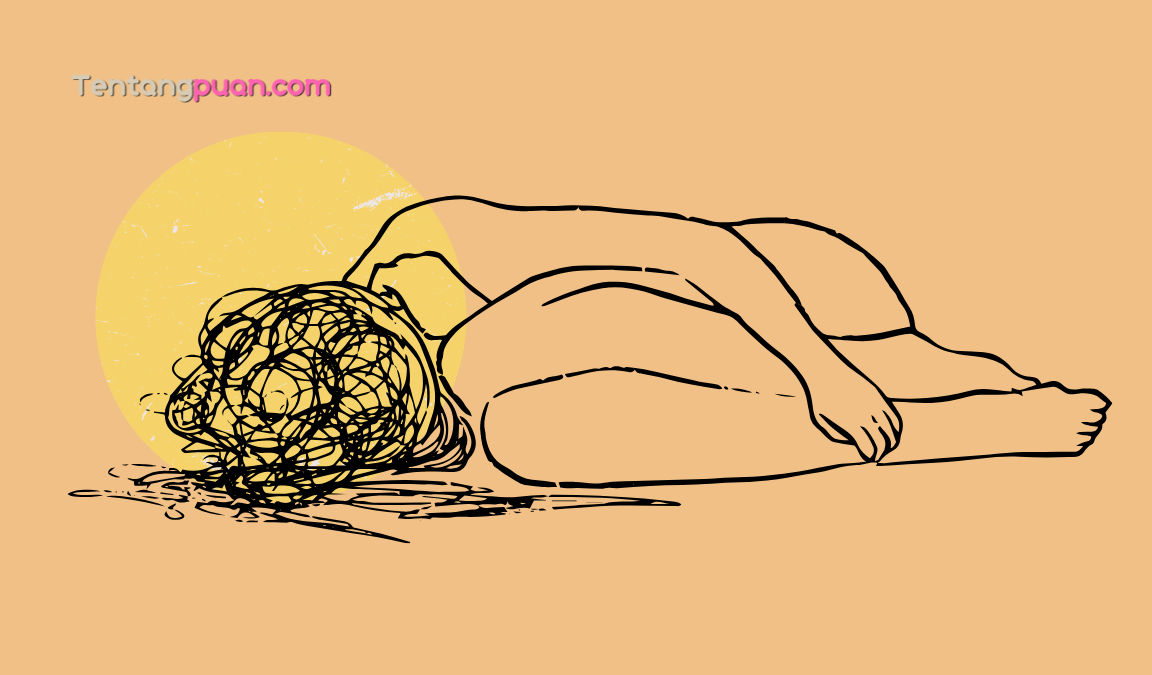TENTANGPUAN.com – Serial Perempuan Kecil, Adat Besar berlanjut. Di tanah tempat Desi pernah dikutuk oleh dosa yang bukan miliknya sendiri, kini tumbuh kisah lain. Adalah Cici (bukan nama sebenarnya), membawa kisah tentang cinta yang dipersalahkan. Cinta yang dianggap terlarang hanya karena dunia belum sepenuhnya berpihak pada perempuan.
Tepat di depan rumah Desi, keheboan muncul ketika ibu Cici menghampiri para ibu di komplek yang tengah asik mengobrol. Wajahnya tegang.
Ada ketakutan yang mencoba ia sembunyikan di balik senyum kaku. Ia mengira, seperti dulu Desi, kini giliran anaknya yang menjadi bahan gosip.
Ketika Cinta Menjadi Dosa Baru
Sudah sebulan Cici kembali ke rumah setelah sebelumnya menempuh kuliah di Gorontalo. Ia mahasiswa Universitas Ichsan, baru mau semester dua.
Oleh ibunya, Cici dikatakan sedang sakit maag. Namun, perut yang makin membesar membuat rahasia itu tak lagi bisa disembunyikan. Belakangan, barulah terungkap bahwa Cici sedang mengandung.
Kabar itu beredar cepat di kampung. Bisik-bisik tentang “anak perempuan yang mempermalukan keluarga” mulai terdengar.
Seperti kisah Desi, Cici juga menjadi bahan perbincangan, bukan karena siapa dirinya, tetapi karena apa yang dianggap telah ia lakukan.
Sejak saat itu, ibunya jarang keluar rumah. Ayahnya memilih diam, menunduk setiap kali bertemu tetangga. Mereka berdua memikul rasa malu yang sesungguhnya tak seharusnya ditanggung. Dan di tengah semua itu, Cici tetap bungkam.
“Waktu itu aku minum minuman bersoda, aku tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi,” ucap Cici pelan, hampir berbisik.
Cici tidak memiliki pacar. Lelaki yang menghamilinya hanya teman, yang sebenarnya sudah bertunangan dan akan segera menikah. Lima tahun lebih tua dari dirinya.
Cici tak sepenuhnya paham apa yang terjadi malam itu. Ia tidak pernah menyebut dirinya diperkosa, tapi juga tidak sadar sepenuhnya ketika peristiwa itu berlangsung.
Ia kebingungan, ketakutan, dan merasa bersalah pada hal yang bahkan tidak ia pahami. Tak seorang pun datang menenangkannya. Sebaliknya, semua mata mengarah padanya, seolah tubuhnya adalah bukti kejahatan yang tak terampuni.
Pernikahan Sebagai Hukuman
Di tengah tekanan sosial dan amarah keluarga, keputusan diambil cepat. Cici harus dinikahkan. Tidak ada ruang untuk bertanya apakah ia setuju, apakah ia siap, atau apakah ia mengerti konsekuensinya. Yang penting, aib harus segera ditutup.
Padahal, usia Cici belum genap delapan belas tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Namun, di kampung ini, adat seringkali lebih kuat daripada hukum.
“Lebih baik menikah daripada menanggung malu,” begitu alasan yang terus diulang.
Keluarga lelaki yang menghamilinya datang membawa uang adat. Karena berasal dari luar kampung, jumlahnya diperbesar, bukan sebagai bentuk tanggung jawab, melainkan sebagai harga atas kehormatan yang dianggap tercoreng. Tidak ada ruang bagi Cici untuk bersuara. Ia hanya duduk diam di kursi pelaminan, dengan mata kosong, saat ijab kabul dilangsungkan.
Tak ada yang menyadari bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah bentuk pemaksaan terhadap anak di bawah umur.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas menyebut: setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pemaksaan perkawinan. Tapi di kampung ini, hukum negara kalah oleh rasa malu dan keinginan menjaga nama baik keluarga.
Tiga bulan setelah pernikahan itu, lelaki yang kini disebut suaminya pergi. Katanya mencari pekerjaan di luar daerah. Ia tak pernah kembali. Enam bulan kemudian, Cici melahirkan seorang bayi laki-laki. Di usia yang baru 18 tahun, Cici sudah menyandang dua status yang berat: istri dan ibu, tanpa pendamping, tanpa perlindungan.
Kini, setiap kali ia menimang bayinya di beranda rumah, pandangan orang-orang masih menusuk. “Itu Cici,” bisik mereka, “yang dulu merebut tunangan orang.” Tidak ada yang menyebutnya korban. Tidak ada yang bicara soal hukum. Yang ada hanya stigma.
Cici kini berhenti kuliah. Ia tak punya cukup keberanian untuk kembali ke kampus di Gorontalo. Sementara teman-temannya membicarakan skripsi dan magang, ia sibuk menenangkan bayinya yang menangis tengah malam. Hidupnya berhenti di satu titik, di antara rasa malu, kehilangan, dan beban moral yang tak pernah ia pilih.
Namun sesungguhnya, Cici bukanlah pelaku dosa. Ia adalah korban dari sistem yang gagal melindunginya. Korban dari ketidaktahuan, dari ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan, dari adat yang lebih cepat menghakimi ketimbang memahami.
Bila hukum berjalan semestinya, Cici berhak mendapatkan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan pendidikan lanjutan. Kasusnya semestinya dikategorikan sebagai eksploitasi seksual terhadap anak, bukan sekadar “aib keluarga”. Tapi kenyataan di lapangan sering berbeda: korban perempuan harus belajar hidup dengan luka, sementara pelaku berjalan bebas tanpa beban.
Kini, dengan mata sayu namun tetap lembut, Cici berkata lirih, “Aku cuma ingin bisa kuliah lagi. Aku tidak marah, cuma capek.”
Kata-kata itu seolah menegaskan satu hal: di balik narasi “cinta terlarang” yang diceritakan banyak orang, sebenarnya ada anak perempuan yang kehilangan masa depan karena sistem yang tak berpihak padanya.
Kisah Cici bukan sekadar tentang cinta atau aib. Ia adalah cermin dari betapa mudahnya masyarakat mengorbankan anak perempuan demi menjaga nama baik dan tradisi. Seperti Desi, Cici hanyalah satu dari banyak perempuan kecil yang tumbuh di bawah bayang-bayang adat besar, yang menuntut kesucian, tapi lupa pada keadilan.
Bersambung di kisah selanjutnya: Denda Adat yang Tak Menghapus Luka