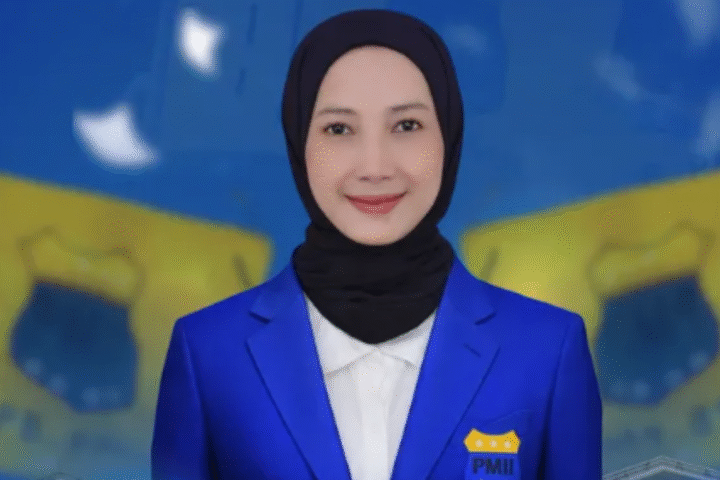TENTANGPUAN.com – Sulawesi Utara kembali diguncang kasus kekerasan seksual (KS) di lingkungan perguruan tinggi. Seorang mahasiswi Universitas Negeri Manado (UNIMA), Evia Mangolo, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Tondano, Selasa (30/12/2025).
Korban diduga mengakhiri hidup akibat trauma berat setelah mengalami pelecehan seksual oleh dosennya.
Peristiwa tragis ini memicu gelombang kecaman dan pernyataan sikap dari berbagai organisasi perempuan, lembaga perlindungan anak, hingga aktivis masyarakat sipil di Sulawesi Utara. Mereka menilai kasus ini sebagai bukti nyata kegagalan kampus dalam melindungi korban kekerasan seksual.
Gerakan Perempuan Sulut: Ada Pembiaran Sistemik di Kampus
Koordinator Gerakan Perempuan Sulut (GPS), Ruth Ketsia, menegaskan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi kerap terjadi karena relasi kuasa yang timpang antara dosen atau pimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswi.
“Relasi kuasa yang timpang, terutama antara dosen atau pimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswi, kerap digunakan untuk menekan dan mengancam korban demi memuaskan nafsu kebejatan seksual,” ujar Ruth dalam pernyataan tertulisnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas meninggalnya Evia Mangolo, yang sebelumnya disebut telah melaporkan dugaan pelecehan seksual ke pihak pimpinan kampus dan Satgas kampus. Namun, laporan tersebut dinilai tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan berpihak pada korban.
GPS juga menyoroti perubahan kebijakan nasional, yakni dicabutnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan digantikan dengan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024, yang tidak lagi secara spesifik menyebut istilah kekerasan seksual.
“Kata seksual dihilangkan. Ini memberi pesan seolah kekerasan seksual bukan persoalan yang mendesak dan serius,” tegas Ruth.
Menurut GPS, perubahan regulasi tersebut berdampak pada melemahnya komitmen kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk di UNIMA.
Satgas Dinilai Tidak Berperspektif Korban
Berdasarkan informasi dari pihak kampus dan pendamping hukum, GPS mengungkapkan bahwa terduga pelaku merupakan dosen yang disebut telah berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi lain dan bahkan dijuluki sebagai predator.
“Informasi dari LBH Manado yang pernah mendampingi korban serupa di kampus yang sama menyebutkan bahwa Satgas kampus tidak memiliki perspektif korban,” kata Ruth.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tragedi yang menimpa Evia Mangolo bukan peristiwa tunggal, melainkan akibat dari pembiaran yang berlangsung dalam jangka waktu lama.

Desakan Proses Hukum dan Kecaman dari Berbagai Pihak
GPS menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang harus diproses secara hukum sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Kasus kekerasan seksual tidak cukup diselesaikan secara internal kampus. Satgas harus mendampingi korban untuk melapor ke aparat penegak hukum dan memastikan ruang aman bagi korban,” tegas Ruth.
GPS secara khusus mendesak pimpinan UNIMA agar tidak menghambat proses hukum dengan alasan menjaga nama baik institusi.
Kecaman juga datang dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Jull Takaliuang, yang menyatakan duka mendalam atas kematian Evia Mangolo dan menyebut peristiwa ini sebagai lonceng peringatan keras bagi dunia pendidikan.
“Kematian almarhumah Evia Mangolo adalah lonceng peringatan keras bagi UNIMA sebagai lembaga pendidikan tinggi di Sulawesi Utara,” ujar Jull.
Ia menegaskan bahwa jika benar terduga pelaku sebelumnya pernah mendapatkan sanksi namun tidak berubah, maka tidak ada alasan lagi untuk melindungi pelaku.
“Tidak boleh ada dosen yang bersembunyi di balik jabatan dan kewenangannya. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” katanya.
Jull juga mendesak UNIMA agar tidak bersikap pasif dan segera membentuk tim khusus untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain.
“Satgas TPKS jangan hanya formalitas, tetapi harus difungsikan untuk membuka ruang kesaksian korban-korban lain yang mungkin masih takut dan malu,” tambahnya.
Aktivis perempuan Vivi George dari Swara Parangpuang Sulut turut bereaksi dan menyebut kasus ini sebagai refleksi pahit di penghujung tahun 2025.
“Kampus tidak lagi aman. Ini realita. Siapa pun kita harus berani speak up dan bersama-sama mengawal kampus agar bebas dari segala bentuk kekerasan,” tegas Vivi.
Ia juga menyoroti tingginya kerentanan perempuan dan anak, baik di ranah domestik maupun ruang publik, serta perlunya pengaktifan kembali rumah aman bagi korban kekerasan.
Tuntutan Transparansi Penegakan Hukum
Sejumlah organisasi, termasuk GPS, Komnas Perlindungan Anak Sulut, Swara Parangpuang Sulut, dan jejaring pendamping korban, mendesak Polda Sulawesi Utara untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan hingga keluarga korban mendapatkan keadilan.
“Kepergian Evia harus menjadi pengingat bahwa negara, kampus, dan aparat penegak hukum tidak boleh lagi abai terhadap jeritan korban,” ujar Ruth.
GPS menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman maksimal.
“Hari ini Sulawesi Utara berduka. Namun duka ini harus berubah menjadi keberanian kolektif untuk menghentikan kekerasan seksual. Zero tolerance,” pungkas Ruth.
Secara hukum, dugaan kekerasan seksual yang dialami almarhumah Evia Mangolo memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini secara tegas mengakui bahwa kekerasan seksual kerap terjadi dalam relasi kuasa yang timpang, termasuk di lingkungan pendidikan.
Pasal 4 UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan, antara lain pelecehan seksual fisik dan nonfisik, perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan secara paksa, serta tindakan yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa atau situasi ketergantungan korban terhadap pelaku.
Pasal 13 UU TPKS mengatur pelecehan seksual nonfisik, termasuk perbuatan bernuansa seksual melalui ucapan, gestur, atau tindakan lain yang membuat korban merasa terhina, terintimidasi, atau tidak berdaya. Dalam konteks kampus, tindakan dosen yang diduga menjanjikan perubahan nilai akademik untuk menekan mahasiswi termasuk bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Relasi kuasa juga menjadi keadaan yang memberatkan. Pasal 15 huruf f UU TPKS menyebutkan bahwa pidana dapat diperberat apabila tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan, kepercayaan, atau kewenangan terhadap korban, termasuk pendidik atau tenaga kependidikan terhadap peserta didik.
Selain pidana pokok, Pasal 18 UU TPKS memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, termasuk larangan pelaku menjalankan profesi yang berkaitan langsung dengan korban.
UU TPKS juga secara tegas melarang penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme damai atau penyelesaian internal semata. Pasal 23 menyatakan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual tidak boleh dilakukan melalui perdamaian jika menghilangkan hak korban atas keadilan dan pemulihan.
Dalam aspek perlindungan korban, Pasal 67 hingga Pasal 70 UU TPKS menjamin hak korban atas pendampingan hukum, layanan psikologis, perlindungan dari ancaman, serta pemulihan. Perguruan tinggi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan korban mendapatkan akses atas hak-hak tersebut, termasuk mendorong pelaporan ke aparat penegak hukum.
Dengan merujuk pada UU TPKS, desakan berbagai organisasi perempuan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kematian Evia Mangolo tidak hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga mandat hukum. Kegagalan menangani laporan korban secara serius membuka ruang evaluasi terhadap tanggung jawab institusional kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.