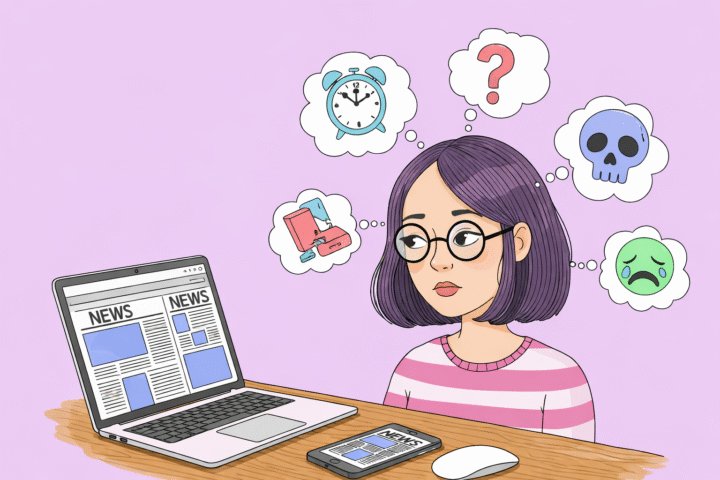TENTANGPUAN.com – Sebuah berita dengan judul “Dua Gadis MiChat Terjaring Operasi Rutin Polres Boltim” sempat beredar dan menjadi perbincangan di kalangan jurnalis lokal.
Sekilas, judul itu tampak informatif, polisi melakukan operasi, ada penangkapan, ada aplikasi daring yang digunakan untuk praktik prostitusi.
Namun jika dicermati lebih dalam, di balik susunan kata itu tersimpan masalah serius dalam cara media memperlakukan perempuan dan anak sebagai subjek pemberitaan.
Ketika Judul Menyudutkan Korban
Kata “Dua Gadis MiChat” memberi kesan bahwa yang menjadi sorotan utama adalah perempuan — bahkan tanpa menyebut bahwa mereka masih berusia belasan tahun. Dalam konteks pemberitaan, label seperti ini bukan hanya menggiring opini publik, tetapi juga menghapus fakta bahwa yang terlibat sebenarnya adalah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial.
Padahal, secara hukum, anak di bawah umur tidak dapat dianggap sebagai pelaku prostitusi. Mereka adalah korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual.
Dengan menonjolkan identitas korban, bahkan secara tidak langsung melalui penyebutan aplikasi atau lokasi, media justru memperkuat stigma dan reviktimisasi, atau penyalahgunaan narasi yang membuat korban kembali disalahkan.
Diksi “terjaring operasi” juga menimbulkan persoalan lain. Ia menempatkan korban seolah-olah sebagai pihak yang bersalah, sementara pelaku utama, yaitu mucikari dan pengguna jasa, tidak mendapat bobot pemberitaan yang sama. Pola seperti ini bukan hanya masalah etika, tetapi juga berpotensi menormalkan kekerasan berbasis gender dan eksploitasi seksual di ruang publik.
Dalam banyak kasus, bahasa jurnalistik yang bias terhadap perempuan kerap lahir dari kebiasaan redaksi yang lebih mengutamakan sensasi daripada substansi. Padahal, tugas media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendidik publik agar memahami persoalan dengan adil dan berperspektif manusiawi.
Bagaimana Seharusnya Media Menulis
Untuk membangun pemberitaan yang adil gender, media perlu memusatkan perhatian pada pelaku eksploitasi, bukan pada korban. Judul berita, misalnya, bisa diarahkan pada tindakan hukum yang dilakukan polisi terhadap pelaku, bukan pada anak atau perempuan yang menjadi korban.
Beberapa contoh judul yang lebih tepat di antaranya:
- “Polres Boltim Ungkap Kasus Eksploitasi Seksual Anak Lewat Aplikasi Online”
- “Dua Anak Diduga Jadi Korban Eksploitasi Seksual, Polisi Tangkap Pelaku”
- “Kasus Eksploitasi Seksual Anak Terungkap di Boltim, Polisi Usut Jaringan Online”
Pilihan kata seperti “korban”, “eksploitasi seksual”, dan “anak” menegaskan posisi yang tepat dalam bingkai hukum dan etika.
Mendorong Perspektif Perlindungan Anak
Lebih jauh lagi, jurnalis juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan prinsip perlindungan identitas anak. Itu berarti menghindari penyebutan lokasi spesifik, ciri-ciri fisik, atau detail lain yang bisa menyingkap identitas korban. Dalam konteks ini, kerja jurnalistik bukan sekadar melaporkan, tetapi juga melindungi.
Media yang berpihak pada korban sesungguhnya sedang membangun ruang publik yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak. Sebaliknya, media yang abai pada perspektif kesetaraan justru berkontribusi pada pelanggengan kekerasan simbolik, kekerasan yang lahir dari kata-kata.
Menulis berita tentang kekerasan seksual, prostitusi daring, atau kasus eksploitasi anak membutuhkan kepekaan. Setiap kata bisa membentuk persepsi, dan setiap persepsi bisa menentukan apakah korban mendapat dukungan atau justru dikucilkan.
Karena itu, jurnalisme sejati tidak berhenti pada kecepatan memberitakan, melainkan pada keberpihakan terhadap mereka yang lemah.
Dalam konteks ini, menulis dengan empati dan kesadaran gender adalah bentuk tanggung jawab moral, sekaligus komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang menjadi korban dua kali: di dunia nyata dan di halaman berita.