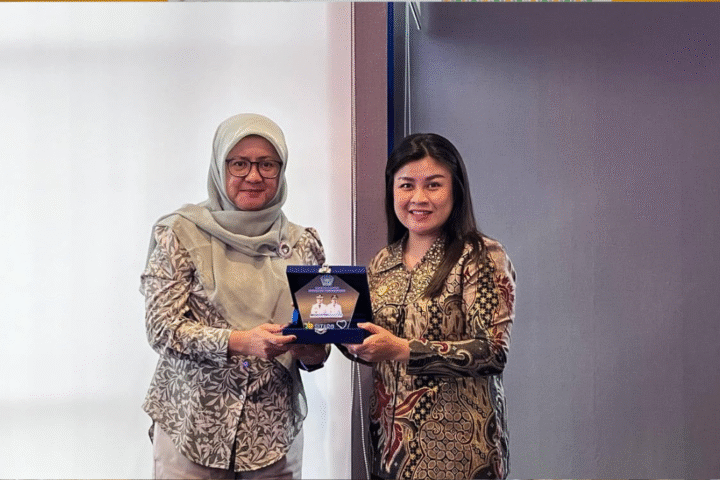TENTANGPUAN.com – Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Provinsi Sulawesi Utara, mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah cepat.
Dalam tiga tahun terakhir, tercatat sebanyak 92 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan.
Sebagai respons, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sitaro memperkenalkan program inovatif bernama Gerakan Cepat Tanggapi dan Dampingi (Gercep Tada).
Inovasi ini lahir dari kegelisahan atas tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terus terjadi di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Dinas P3AP2KB Sitaro sejak tahun 2022 hingga 2024, tercatat 53 kasus perkosaan, 26 kasus percabulan, empat anak yang berhadapan dengan hukum, serta dua kasus video asusila.
Menurut Kepala Dinas P3AP2KB, Febiola Papona, terdapat tiga persoalan utama yang mengemuka, yakni masih banyak kasus kekerasan yang tidak terlapor, sulitnya akses ke layanan karena faktor geografis Sitaro yang terdiri dari pulau-pulau, serta lambannya penanganan kasus di kepolisian.
“Karena itu, dicetuskan inovasi Gercep Tada, dengan tujuan agar korban mendapatkan layanan, penanganan, dan pendampingan secara cepat, tepat dan komprehensif dengan pemulihan korban secara fisik dan mental,” kata Papona, Minggu, (27/4/2025).
Ia menegaskan, inovasi ini mengacu pada Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
“Nantinya tidak hanya untuk anak tetapi berlaku juga untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, karena datanya juga cukup tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Papona menjelaskan bahwa mekanisme kerja Gercep Tada meliputi dua jalur pengaduan, yaitu layanan langsung di kantor Dinas P3AP2KB dan melalui aplikasi media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Messenger, telepon maupun SMS. Setelah laporan diterima, akan dilakukan verifikasi, penjangkauan, dan konferensi pengelolaan kasus.
Empat tahapan penanganan akan dilalui, yakni penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, dan rujukan, sebelum dilanjutkan ke konferensi kasus.
“Untuk kasus yang terselesaikan maka kita masuk tahap pengakhiran, sementara untuk kasus yang belum selesai akan kembali ke tahap melakukan penjangkauan,” jelas Papona.
Setiap kasus akan dikodekan, dengan kode A untuk kasus kekerasan terhadap anak, dan kode P untuk kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Warga bisa mengunjungi akun kami di Facebook atau datang ke kantor untuk bisa mengetahui secara detail,” ajaknya.
Selain itu, data nasional dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga saat ini, tercatat 2.777 kasus kekerasan pada anak usia 13 hingga 17 tahun, 1.554 kasus pada anak usia 6 hingga 12 tahun, dan 601 kasus pada anak usia di bawah 6 tahun.
Psikolog: Kekerasan Anak Banyak Dilakukan Orang Terdekat
Sementara itu, Psikolog Klinis dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Indria Laksmi Gamayanti, mengecam tingginya kasus kekerasan anak di Indonesia.
“Kekerasan pada anak bisa dilakukan oleh siapa saja. Sayangnya menurut penelitian banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa terdekat yang justru seharusnya bisa menjadi pelindung dari anak tersebut,” kata Gamayanti dalam sebuah artikel di website UGM.
Gamayanti menguraikan tiga bentuk kekerasan pada anak, yakni kekerasan fisik, kekerasan emosi, dan kekerasan seksual.
Ia menekankan, saat anak mengalami kekerasan fisik atau seksual, biasanya disertai pula dengan kekerasan emosi.
Menurutnya, kekerasan emosi menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi namun sering kali tidak disadari.
“Kondisi di mana anak mendapatkan ujaran kemarahan, kebencian, penghinaan, dan bentuk kekerasan verbal lainnya,” ujarnya.
Ironisnya, pelaku kekerasan justru banyak berasal dari orang tua atau orang terdekat anak.
“Secara psikologis, pelaku kekerasan cenderung memiliki gangguan kesehatan mental dalam dirinya sendiri. Faktor pemicu dari tendensi tindakan kekerasan pada pelaku juga bermacam-macam, mulai dari kesiapan mental orang tua, kondisi ekonomi, hingga pengalaman kekerasan serupa di masa kecil,” jelas Gamayanti.
Ia menyebut, orang dewasa yang melakukan kekerasan pada anak biasanya adalah individu yang tidak matang secara emosi dan mungkin pernah mengalami kekerasan di masa kecil.
“Bayangan masa lampau atau trauma masa kecil orang tua memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan serupa atau lebih terhadap anaknya,” tutur Gamayanti.
Dalam dunia psikologi, pengalaman kekerasan di masa kecil diklasifikasikan sebagai Adverse Childhood Experiences (ACEs). Dampaknya, anak-anak yang mengalami ACEs berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental dan kecenderungan melakukan kekerasan ketika dewasa.