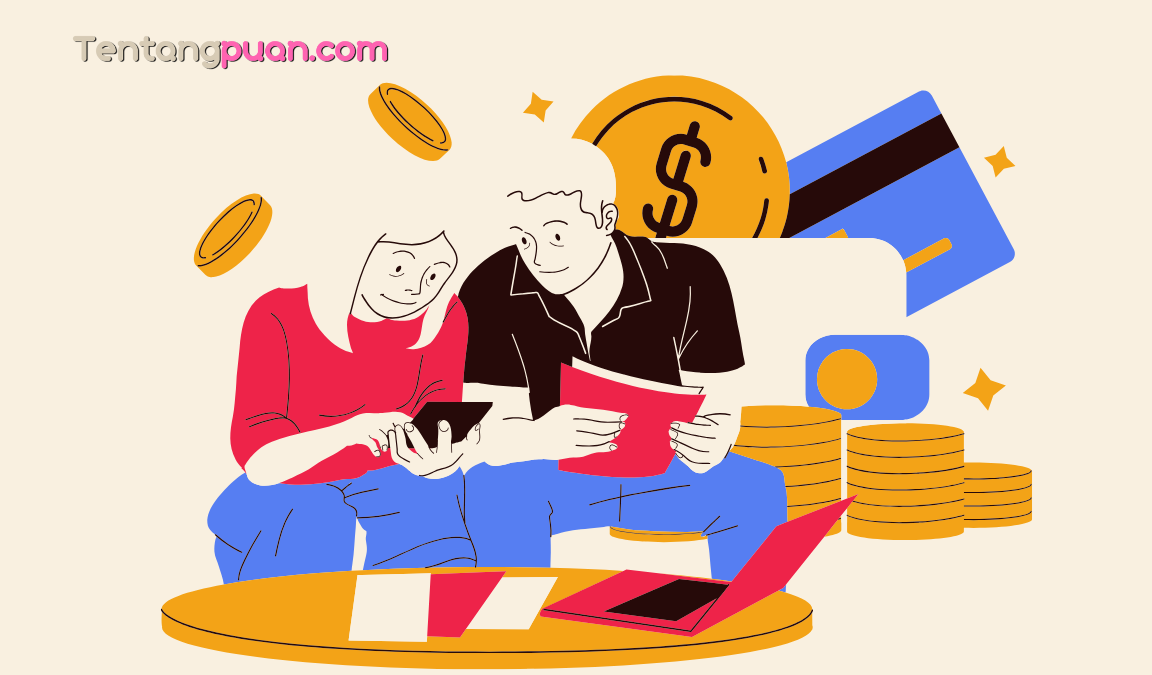TENTANGPUAN.com – Setiap awal bulan deretan notifikasi dari perbankan kerap membuat orang merasa lega. Gaji sudah masuk. Namun tak lama berselang, rasa lega itu berganti dengan kebingungan, ke mana uang itu pergi? Tanpa disadari, separuhnya sudah habis hanya dalam hitungan minggu, bahkan hari. Fenomena ini terjadi pada banyak orang, dan akar persoalannya sering kali bukan pada jumlah uang, melainkan pada kemampuan memprioritaskan penggunaannya.
Kemampuan memprioritaskan uang adalah keterampilan yang tak semua orang miliki. Ia bukan sekadar soal mencatat pengeluaran atau menabung di akhir bulan, tetapi kemampuan untuk menimbang mana yang lebih penting antara kebutuhan dan keinginan. Ketika kemampuan itu lemah, uang kehilangan arah, dan hidup ikut terseret dalam ketidakpastian.
Seseorang yang tidak bisa menetapkan prioritas keuangan cenderung menghabiskan uang pada hal-hal yang memberi kepuasan sesaat. Belanja impulsif, nongkrong berlebihan, atau mengikuti tren digital menjadi bentuk pelarian yang umum. Namun di balik kesenangan singkat itu, ada dampak panjang yang sering diabaikan.
Dampak pertama tentu saja muncul pada stabilitas finansial. Tanpa prioritas, tabungan sulit terbentuk, investasi tak pernah dimulai, dan utang menjadi jalan pintas yang berulang. Banyak keluarga yang akhirnya hidup dari utang ke utang, bukan karena penghasilan yang terlalu kecil, tetapi karena pola pengeluaran yang tidak tertata.
Masalah keuangan ini kemudian menjalar ke sisi psikologis. Seseorang yang keuangannya tidak terkendali akan lebih rentan mengalami stres, cemas, bahkan depresi ringan. Rasa bersalah karena tidak bisa mengatur uang dengan baik juga memicu penurunan harga diri. Tak jarang, mereka menutupinya dengan kembali berbelanja atau bersenang-senang — sebuah lingkaran yang terus berputar.
Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Consumer Research (2020), disebutkan bahwa ketika seseorang menghadapi keterbatasan anggaran, mereka secara alami mulai memprioritaskan pengeluaran ke hal-hal yang paling penting. Studi ini berjudul Preference Refinement after a Budget Contraction, dan menyoroti bagaimana krisis keuangan justru bisa memaksa orang menjadi lebih selektif. Namun, jika tidak ada kesadaran untuk memilah sejak awal, pengeluaran cenderung liar dan tidak terkendali.
Penelitian lain yang diterbitkan tahun 2023 di Frontiers in Psychology menemukan bahwa individu yang mengaitkan harga diri mereka dengan kondisi keuangan (disebut financial contingent self-worth) lebih mudah mengalami konflik antara keinginan untuk membelanjakan dan kebutuhan untuk menabung. Mereka merasa harus “terlihat mampu” agar dihargai. Akibatnya, mereka lebih rentan pada pembelian kompulsif dan stres finansial yang lebih tinggi.
Dari dua penelitian tersebut, tampak jelas bahwa masalah prioritas uang bukan hanya soal matematika, tetapi juga psikologi dan sosial. Banyak orang membelanjakan uang bukan karena butuh, tapi karena ingin diakui. Dalam masyarakat yang semakin konsumtif, keinginan untuk tampil layak di mata orang lain sering kali mengalahkan kebutuhan dasar.
Di tingkat keluarga, ketidakmampuan memprioritaskan keuangan dapat menimbulkan konflik yang serius. Suami-istri bisa berselisih paham karena uang belanja tidak cukup atau karena keputusan finansial yang diambil sepihak. Anak-anak pun bisa menjadi saksi ketegangan yang seharusnya bisa dihindari.
Bahkan di lingkungan sosial, perilaku keuangan yang tidak teratur bisa berimbas pada reputasi seseorang. Mereka yang kerap meminjam uang tanpa mampu mengembalikan, atau terus menunda tanggung jawab finansial, perlahan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga relasi sosial.
Kondisi ini sebenarnya bisa dihindari. Banyak pakar keuangan menekankan pentingnya membuat daftar prioritas. Kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan harus selalu di posisi teratas. Baru setelah itu, kebutuhan sekunder dan hiburan bisa disesuaikan dengan kemampuan.
Langkah sederhana seperti mencatat pengeluaran harian dan menentukan batas maksimal konsumsi bulanan bisa membantu seseorang melihat gambaran besar keuangannya. Dengan begitu, uang tidak lagi bergerak tanpa arah. Setiap rupiah memiliki tujuan dan alasan.
Selain pencatatan, aspek mental juga perlu diperhatikan. Disiplin dalam mengelola keuangan membutuhkan kesadaran emosional. Banyak pengeluaran impulsif yang lahir bukan dari kebutuhan, tetapi dari rasa bosan, stres, atau keinginan diakui. Menyadari sumber emosional dari keputusan finansial bisa membantu seseorang menunda, bahkan menghindari pengeluaran yang tidak perlu.
Di era media sosial, tekanan konsumsi semakin kuat. Gaya hidup digital membuat kita mudah tergoda untuk meniru orang lain, membeli barang karena “semua orang punya”, atau berlibur demi konten. Dalam konteks ini, memprioritaskan uang menjadi bentuk perlawanan kecil terhadap arus konsumsi massal.
Bagi sebagian orang, membuat prioritas uang juga berarti belajar mengatakan “tidak”. Tidak pada tawaran kredit yang menggiurkan, tidak pada ajakan konsumsi berlebihan, dan tidak pada pembelian yang tidak membawa nilai jangka panjang. Keputusan-keputusan kecil itu, jika dilakukan konsisten, akan menciptakan kestabilan besar di masa depan.
Pemerintah dan lembaga keuangan di Indonesia kini mulai mendorong literasi finansial sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan menghitung bunga atau membuat anggaran. Literasi sejati adalah ketika seseorang paham bagaimana uang bisa menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan sumber masalah baru.
Pada akhirnya, uang hanyalah alat. Ia bisa membawa rasa aman, tetapi juga bisa menjerumuskan jika tidak diarahkan dengan bijak. Memprioritaskan penggunaan uang berarti belajar mengarahkan hidup — karena setiap keputusan finansial, sekecil apa pun, adalah cermin dari nilai dan tujuan yang kita pegang.