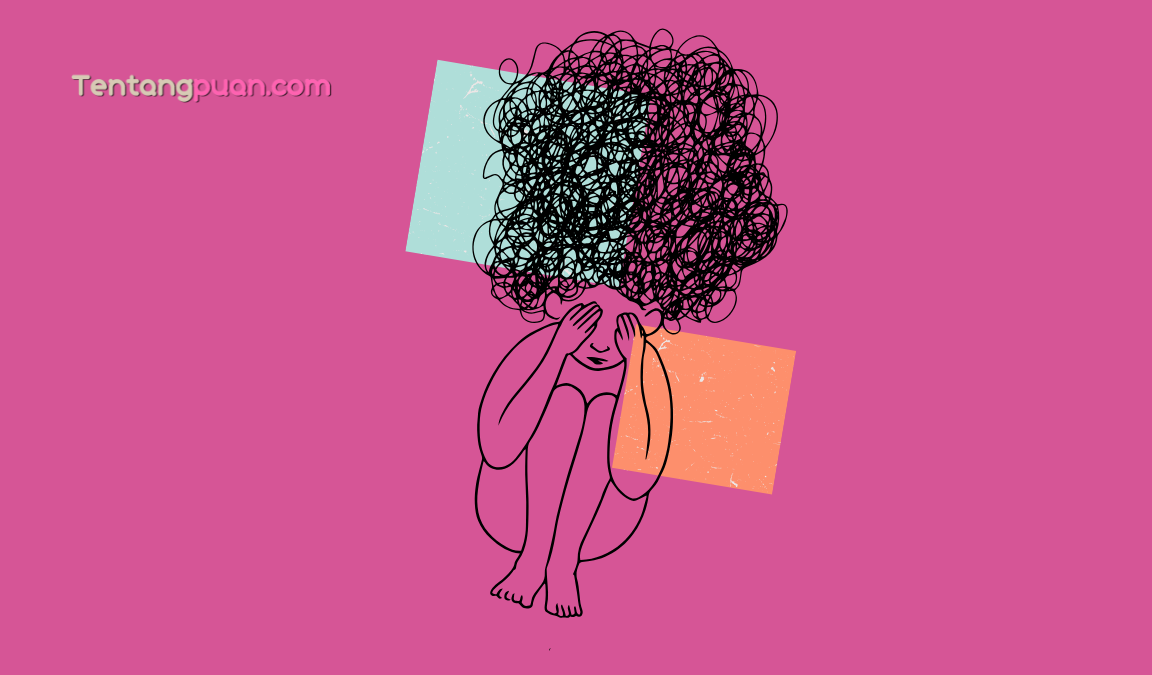TENTANGPUAN.com – Hari itu, jelang akhir tahun 2024, Indry (bukan nama sebenarnya) duduk bersimpuh di ruang tamu rumahnya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya berhias gincu merah darah, dan kain berwarna emas membalut tubuh mudanya.
Ia tampak seperti pengantin, tapi tidak ada pesta, tidak ada tawa. Hanya tatapan kosong dari seorang anak perempuan yang terpaksa menyambut tetua adat.
Para tetua datang membawa amplop berisi uang denda adat sebesar Rp30 juta. Uang itu disebut sebagai “pembayaran adat” atas aib yang dianggap mencoreng nama keluarga.
Tidak ada cincin, tidak ada janji. Hanya uang dan segenggam beban yang diwariskan kepada gadis berusia 18 tahun itu.
Indry tak banyak bicara. Sejak pertemuan di Balai Kelurahan, ia belum lagi melihat wajah laki-laki yang membuatnya berbadan dua.
Laki-laki itu dulu kekasihnya–sosok yang memberinya janji, perhatian, dan cinta. Tapi janji itu lenyap begitu ia tahu bahwa laki-laki tersebut sudah beristri.
Yang lebih menyakitkan, perempuan yang menjadi istri laki-laki itu ternyata tenaga kesehatan. Dialah yang menyarankan Indry untuk meminum pil penggugur kandungan.
“Supaya tidak mempermalukan siapa pun,” katanya dingin. Indry hanya menangis.
Namun Indry menolak. Bukan karena ia siap menjadi ibu, tetapi karena ia takut mati. Ia pernah mendengar cerita gadis lain yang kehilangan nyawa karena aborsi ilegal.
Sejak itu, ia menyembunyikan perutnya dengan pakaian longgar, berusaha menutupi rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan.
Ketika kabar kehamilannya tersebar, warga desa mulai berbisik. “Anak siapa?” “Bagaimana orang tuanya bisa membiarkan?” Kalimat-kalimat itu menjadi pisau yang menoreh hati ibunya setiap kali ia keluar rumah.
Hukum, Adat, dan Perempuan yang Jadi Korban
Dalam sidang adat yang digelar di rumah kepala lingkungan, keluarga Indry hanya bisa pasrah. Sebagian tetua menilai satu-satunya jalan adalah menikahkan mereka. Tapi pernikahan itu tak pernah terjadi. Laki-laki itu menghilang dan tak pernah kembali.
“Sudah, kita tuntut saja denda adat,” kata salah satu tetua.
Kalimat itu seperti vonis. Uang menggantikan tanggung jawab. Laki-laki itu tak perlu hadir, cukup mengirim uang sebagai bentuk “pembersihan” nama baik keluarga perempuan.
Bagi Indry, Rp30 juta itu tak pernah bisa membeli kembali masa depan yang dicurinya.
Ia harus menanggung beban sosial seorang ibu muda tanpa suami. Namun yang paling berat adalah bagaimana masyarakat masih menilainya sebagai penyebab aib, bukan korban.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU ini juga menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan eksploitasi. Tapi dalam kasus Indry, hukum adat sering kali lebih cepat bertindak, meski tak selalu adil bagi korban.
Sebuah riset dari Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat bahwa dalam kasus kekerasan seksual di daerah pedesaan, sekitar 47% diselesaikan melalui mekanisme adat atau kekeluargaan, dan dari jumlah itu, sebagian besar berakhir tanpa keadilan bagi perempuan.
Uang denda dianggap cukup menggantikan rasa malu, tapi tidak pernah mengobati luka korban.
Ibu Indry mengaku sempat berpikir untuk menggugurkan kandungan anaknya.
“Saya takut orang bilang anak saya pelakor,” katanya pelan.
Tapi ia mengurungkan niatnya karena takut dosa dan sanksi sosial. Ia memilih mendampingi Indry menanggung semuanya, termasuk tatapan sinis tetangga.
Kini, setiap pagi Indry mengantar anaknya ke rumah ibunya sebelum berangkat kuliah. Ia bersyukur masih bisa melanjutkan pendidikan, meski dengan langkah tertatih.
“Kalau saya berhenti, saya akan kalah,” katanya.
Namun bayangan masa lalu masih kerap menghantui. Setiap kali melihat perempuan bersanggul di acara pernikahan, hatinya nyeri. Ia teringat hari ketika dirinya dipaksa berbusana pengantin tanpa pernikahan.
Adat yang semestinya menjaga kehormatan perempuan justru membuatnya terpenjara dalam stigma. Ia tidak hanya kehilangan masa remaja, tapi juga haknya untuk memilih.
Bagi keluarga laki-laki, urusan itu sudah selesai. Mereka sudah membayar denda adat. Tapi bagi Indry, hidupnya baru saja dimulai, hidup yang harus dihadapi dengan anak kecil di pelukannya dan pandangan dunia yang masih menilai perempuan dari kesucian, bukan keberanian bertahan.
“Orang bilang saya sudah kotor,” katanya lirih, “padahal saya hanya korban dari janji yang tak ditepati.”
Masa Depan yang Ingin Ditebus
Rumah Indry berdiri tak jauh dari rumah Desi dan Cici, dua gadis lain yang kisahnya juga pernah diguncang oleh adat. Di antara tawa anak-anak kecil yang bermain di halaman, mereka bertiga terkadang duduk bersama, berbagi cerita tentang luka yang sama.
Mereka percaya bahwa adat bisa berubah, jika ada keberanian untuk menafsirkan ulang maknanya. “Adat bukan untuk menghukum perempuan,” kata Indry, “tapi seharusnya untuk melindungi mereka.”
Kisah Indry adalah kisah banyak anak perempuan lainnya di pelosok negeri, mereka yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, menanggung malu atas kesalahan yang bukan sepenuhnya milik mereka.
Namun dari balik luka itu, Indry tumbuh menjadi simbol perlawanan sunyi, seorang ibu muda yang memilih tidak menyerah pada nasib, meski adat dan masyarakat belum sepenuhnya berpihak padanya.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan bagian dari serial liputan khusus “Perempuan Kecil, Adat Besar” yang menyoroti nasib anak perempuan dalam sistem sosial-budaya di Kotamobagu dan sekitarnya.